Membaca Secuil Goenawan Mohamad
Selasa
lalu (22/5), seusai kuliah Perkembangan Sastra Indonesia, saya iseng datang ke
Perpustakaan Pusat UI—karena fakultas saya tidak punya perpustakaan sendiri—untuk
mencari bacaan yang sekiranya enak dibaca. Karena akhir-akhir ini tertarik
dengan ekonomi, saya mencari buku Adam Smith, The Wealth of Nations. Tersedia di katalog daring tidak selalu
berarti tersedia di rak. Buku tersebut tidak ada di sana*. Saya pun kembali ke
katalog daring. Saya mencari buku lain, buku
Goenawan Mohamad. Dalam daftar yang muncul, tampak judul Potret Seorang Penjair Muda sebagai si Malin Kundang. Saya segera
ke rak nomor 899.22.
Potret Seorang
Penjair Muda sebagai si Malin Kundang ternyata buku yang cukup tipis, tidak
sampai seratus halaman. Saya mendapatkan cetakan Pustaka Jaya bertahun 1972.
Dalam buku ini, Goenawan Mohamad (GM) menggunakan tulisan model Ejaan Soewandi.
Oh, ya, dalam tulisan ini, saya akan mengutip beberapa pernyataan GM yang ada
di buku tersebut. Agar menyesuaikan, kutipan-kutipan itu nanti akan saya ubah
ke ejaan yang berlaku sekarang, tetapi tidak mengurangkan atau melebihkan kata-katanya.
Buku
tersebut berisi esai-esai GM yang ditulis sekitar tahun ’60-an. Beberapa esai berbentuk
autobiografi—menggunakan sudut pandang orang ketiga, kecuali bagian
pertemuannya dengan Pramoedya Ananta Toer—dan beberapa lainnya berisi
pendapat-pendapatnya, khususnya tentang sastra. Seharusnya buku ini dapat
dijadikan salah satu buku acuan perkuliahan sastra Indonesia. Meskipun tidak
terlalu fokus dengan sastra, buku ini memuat pandangan-pandangan yang penting.
Setelah
masa sastra individualis pada sekitar tahun 1945 yang ditokohi oleh Chairil
Anwar, 1950-an dan setelahnya—sampai beberapa masa—corak sastra mulai berubah. Keyakinan
bahwa sastra tidak dapat dilepaskan dari masyarakat membuat realisme-sosialis
menjadi tema “luhur” yang menjadi acuan tetap. Itulah yang dikritik oleh GM. Ia
berpendapat bahwa sastra tidak akan segar dengan cara seperti itu. Tema-tema
baru justru muncul ketika ada kebebasan individu untuk menyatakan pikirannya.
“Salah
satu kebebasan pertama seorang pencipta adalah kebebasannya dari sikap kolektif
yang mengikat diri, dan bahaya orang yang terlalu memperhatikan “rumus-rumus”
umum yang dikenakan di atas kesadaran keseorangannya ialah terbentuknya diri
dalam lindungan kolektivisme. Hasilnya nanti tidak akan lebih dari hasil tukang
proyeksi “suara umum” dan penyodoran kemutlakan ajaran” (hlm. 23).
Sebenarnya,
apa yang dimaksud “kolektivisme” oleh GM? Bukankah ujung-ujungnya sastra ditulis
oleh individu yang mempunyai sudut pandang sendiri, meskipun temanya serupa?
Namun, berdasarkan pernyataan di atas, GM mengesankan agar pelaku sastra tidak
terjebak dalam tema besar realisme-sosialis untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Tema-tema liar, seperti absurdisme dan surealisme, perlu mendapat
kedudukan dan perlakuan yang sama. Lebih gampangnya, GM menginginkan sastra selalu
melahirkan yang terbaru.
Tahun
1950-an juga muncul kredo bahwa puisi yang bagus adalah puisi yang sulit.
Semakin sulit bahasa yang digunakan, semakin bagus kualitas kepuisiannya. Kredo
tersebut mewujud sebagai karya-karya yang dimuat dalam majalah Kisah, Seni, Budaya, dan
lain-lain. Apakah sejak masa itu puisi seolah-olah menjadi jauh dari konsumsi
publik dan hanya menjadi konsumsi sesama sastrawan, menjadi barang yang
dianggap terlalu mewah dan tidak terjangkau?
Kenyataannya,
kredo tersebut tampak tidak lagi berlaku pada zaman sekarang. Zaman media
sosial membuat puisi menjadi dekat dengan menggunakan bahasa yang mudah
dimengerti atau bahkan terlalu mudah. Namun, dengan bahasa yang mudah, apakah
tingkat kualitas puisi juga menjadi dangkal? Bahasa dengan tingkat kesulitan
tertentu menandakan bahwa pembuatannya tidak main-main. Memilih diksi pun harus
dipikir berulang kali agar langsung mengena ke hati pembaca dan memungkinkan
menghasilkan banyak tafsiran. Akan tetapi, apakah selalu begitu?
GM
tidak hanya mengemukakan pendapat tentang sastra. Ia juga menyinggung masalah
kehampaan yang dihadirkan modernitas. Produk abad ke-20 itu telah menjadi pintu
gerbang menuju keterasingan manusia. Untuk hal itu, ia menulis suatu peringatan
tentang Rabindranath Tagore dalam bab “Mengingat Tagore”. Kreativitas,
kebebasan, spontanitas: itulah hal-hal berharga yang bagi Tagore semakin hilang
di abad ini (Mohamad, 1972: 51). GM mengutip perumpamaan Tagore, yaitu manusia meninggalkan
sarangnya kemudian masuk ke dalam sangkar. Tagore, dalam tulisan GM, menyatakan
bahwa sarang itu sederhana, memiliki hubungan yang mudah dengan langit,
sedangkan sangkar itu kompleks dan mahal, menyisihkan apa yang ada di luarnya.
Perumpaan
dari Tagore tersebut sepertinya tidak hanya berlaku dalam urusan
eksistensialisme manusia, tetapi juga politik. Manusia zaman sekarang berada
dalam kendali birokrasi yang rumit dan bertele-tele, padahal seharusnya tidak
sekompleks atau seformal itu. Politik birokratif adalah buah dari modernitas
dan keterasingan serta jarak turut diciptakan. Saya jadi teringat lagu ‘Di Atas
Meja” dari Payung Teduh. Salah satu liriknya berkata “tak bisa lagi bercerita
apa adanya”. Kealamian semakin pudar kemudian hilang.
Tidak
hanya politik, keterasingan juga terasa dalam hal agama, lebih spesifiknya
kitab suci. GM menyayangkan pemaknaan isi kitab suci yang terlalu di permukaan.
Dengan cara seperti itu, kitab suci menjadi tidak lebih dari sekadar ancaman-ancaman
yang menakutkan. Padahal, jika diselisik sedikit lebih dalam, kitab suci dapat
menjadi isi bagi kekosongan kehidupan manusia. Sudahlah terasing dari alam dan
manusia, kini terasing dari Tuhan pula. Terlalu sering kita diminta untuk takut
kepada-Nya hingga terlalu sering pula kita lupa bahwa kita pun sebenarnya bisa
tertarik dan mencintai-Nya (Mohamad, 1972: 62—63).
Saya
tidak dapat menghindarkan pikiran saya dari orang-orang fanatik agama,
orang-orang yang justru mengotori kulit agama, ketika membaca tulisan GM
sebagaimana dalam kutipan di atas. Setidaknya, jika tidak bisa menjadi manusia
yang baik, tidak perlu membawa-bawa nama Tuhan untuk melakukan hal yang tidak
baik. Taruhannya adalah agama dan seisinya yang dibawa, serta orang-orang yang
tidak seharusnya terkait, juga keterasingan sebagai dampak lanjutnya. Mungkin
agama yang datang secara asing dan dinubuatkan hilang secara asing pula itu tidak
benar-benar menghilangkan diri, tetapi diasingkan oleh orang-orang yang berjalan
terlalu jauh dari dasarnya dan menegakkan fanatik buta.
Hal
yang bisa kita pelajari dari buku itu tidak setipis kelihatannya. GM juga
menceritakan akibat dari gaung “revolusi” yang selalu digelorakan Sukarno, juga
secuil tentang Manifes Kebudayaan. Kritiknya atas kritik sastra pun ada. Selain
itu, seperti yang sempat sedikit saya singgung dalam paragraf ketiga, GM
berbagi kisah pertemuannya dengan Pramoedya Ananta Toer di Pulau Buru. Sebagai
wartawan muda, ia masih malu untuk menanyakan sesuatu dan akhirnya nekat
bertanya. Menggemaskan sekaligus menampar.
*Buku
The Wealth of Nations ternyata ada di
ruang rujukan, lantai IV.
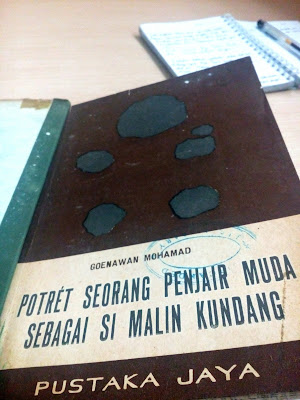
Komentar
Posting Komentar